
Penulis : Rudi Hartono, pemimpin redaksi berdikarionline.com
Angka kemiskinan punya daya politik luar biasa. Bila angka kemiskinan tinggi, daya rusaknya bisa merontokkan popularitas sebuah rezim. Sebaliknya, jika angka kemiskinan berhasil ditekan rendah, maka pemerintah akan dipuji setinggi langit.
Karena itu, dalam statistik, kemiskinan bukan sekedar angka-angka, tetapi juga soal politik. Dengan mengutak-atik metodologi dan alat ukur, politik statistik bisa menjadi senjata untuk menciptakan “gelembung citra” yang diperlukan oleh penguasa untuk meraih popularitas.
Pertengahan Juli lalu, Biro Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka kemiskinan terbaru. Disebutkan, per Maret 2018 angka kemiskinan di Indonesia hanya 9,82 persen. Angka itu diklaim sebagai yang terendah dalam sejarah.
Klaim itu menuai hujan gugatan. Alat ukur kemiskinan BPS, yang hanya mengukur pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, sudah dianggap kadaluarsa dan sangat tidak manusiawi.
Untuk diketahui, garis kemiskinan untuk Maret 2018 ditetapkan Rp 401.220 per kapita per bulan. Artinya, jika seseorang punya pengeluaran di atas Rp 13.674 per hari, maka dia dianggap tidak miskin.
Di sela riuh debat soal ukuran kemiskinan versi BPS itu, ingatan saya terbang ke zaman Hindia-Belanda tahun 1933. Tatkala Bung Karno dan Bung Hatta melancarkan kritik pedas terhadap ukuran kemiskinan versi pemerintah kolonial.
Saat itu, Direktur Binnenlandsch Bestuur (BB)—semacam kementerian dalam negeri—menyampaikan bahwa seorang rakyat Hindia-Belanda bisa hidup dengan 1 ½ sen atau segobang sehari. Angka itu, seperti hitungan BPS hari ini, diambil dari hitungan jumlah kalori yang diperlukan seorang manusia untuk bertahan hidup.
Pernyataan Direktur BB itu membuat Sukarno meradang. Melalui Fikiran Ra’jat, koran yang dipimpinnya, Sukarno melancarkan kritikan keras. Dia menulis artikel berjudul “Orang Indonesia Cukup Nafkahnya Segobang Sehari?”
Lewat artikel penuh amarah itu, Sukarno menuding Direktur BB tidak bisa membedakan antara “cukup” dan “terpaksa”. “Terpaksa hidup dengan sebenggol, dan cukup hidup dengan sebenggol, di antara dua ini adalah perbedaan yang sama lebarnya dengan perbedaan sana dan sini, antara kaum penjajah dan terjajah, antara kaum kolonialisator dan gekoloniseerde,” tulis Sukarno.
Kemarahan Sukarno punya alasan sangat logis. Dia membandingkan nilai sebenggol sehari itu dengan rangsum tahanan di penjara. Menurutnya, sebelum datang zaman meleset (krisis ekonomi Malaise 1930-an), setiap tahanan mendapat rangsum 18 sen sehari. Namun, setelah zaman meleset, setiap tahanan masih mendapat 14 sen per hari. Artinya, rangsum untuk hidup tahanan masih lebih tinggi dibanding dengan standar hidup rakyat kebanyakan versi statistik kolonial.
Tembakan kritik dari Sukarno, juga tokoh-tokoh pergerakan lainnya, mendorong Volksraad untuk memaksa Direktur BB melakukan riset ilmiah atas klaimnya itu. Seturut kemudian, Direktur BB dan Dienst der Volksgezondheid (Departemen Kesehatan Hindia-Belanda) melakukan riset di wilayah Kebumen. Hasinya sudah bisa diduga: 2/12 sen cukup untuk bagi Marhen untuk hidup.
Hasil riset itu tidak membuat kritikan mereda. Kali ini, kritik lebih pedas dan menusuk datang dari pena Bung Hatta. Melalui koran Daulat Ra’jat, 10 Oktober 1933, Bung Hatta menulis artikel berjudul “Krisis Politik Ataukah Anti Kemakmuran Rakyat?”
Di bagian awal artikelnya, Hatta mempertanyakan kebenaran “riset ilmiah” itu. Ia menggugat metodologi riset itu, karena hanya mengambil sampel pada 5 keluarga buruh dan 15 keluarga petani untuk menggambarkan kehidupan keseluruhan rakyat Indonesia.
“Tetapi adakah pemeriksaan yang dilakukan pada satu dua tempat pada 20 rumah tangga dapat dikatakan cermin masyarakat Indonesia,” gugat Hatta.
Selanjutnya, Hatta melancarkan argumentasi satire. Katanya, kalau sekedar untuk bertahan hidup, maka nol persen pun pasti cukup. Sebab, katanya lagi, naluri manusia untuk bertahan hidup akan memaksanya memakan apa saja, termasuk buah kayu, umbut (pucuk kelapa), dan rumput-rumputan.
Yang terjadi kemudian, lanjut Hatta, rakyat bukan lagi mengalami ondervoeding (kurang makan), melainkan onjuistevoeding (salah makan).
Bung Hatta kemudian memperingatkan bahaya dari “quasi wetenschappelijk onderzoek”, sebuah riset yang tampak seolah-olah ilmiah. Termasuk dalam riset terhadap standar hidup layak manusia. Sebuah riset yang diutak-atik metodologinya untuk menggelembungkan citra penguasa, sekalipun diberi gincu ilmiah, tetap saja “riset palsu”.
Lebih lanjut, Bung Hatta tidak setuju dengan penggunaan standar fisiologis untuk mengukur penghidupan ekonomi. Sebab, standar fisiologi hanya mengukur jumlah asupan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia agar tidak mati atau malfungsi. Sebaliknya, penghidupan ekonomi menyangkut hasrat atau keinginan manusia untuk hidup makmur dan bahagia.
Arguementasi Bung Hatta benar adanya. Manusia lahir bukan sekedar bertahan hidup, tetapi untuk maju dan berkembang. Untuk maju dan berkembang, dia butuh pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain.
Karena itu, sebagai antitesa terhadap penggunaan standar “asal bisa hidup” itu, Bung Hatta menawarkan gagasan “politik kemakmuran”, yaitu soal bagimana menaikkan standar penghidupan rakyat.
Politik kemakmuran tidak bicara soal berapa standar pengeluaran agar seseorang tetap hidup, tetapi bagaimana setiap orang bisa berkembang maju, sejahtera dan bahagia.
Nah, agar manusia bisa berkembang maju, setidaknya ada dua hal yang mesti tersediakan. Pertama, kondisi yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas, seperti standar hidup (pangan bergizi, air bersih, perumahan, dll), kesehatan dan pengetahuan. Kedua, kondisi sosial politik yang memungkinkan manusia bisa berkembang, seperti kemerdekaan politik, pengakuan HAM, dan kesetaraan gender.
Saya kira, peluru kritik Bung Karno dan Bung Hatta sangat relevan juga diarahkan ke BPS hari ini. Ukuran kemiskinan versi BPS, yakni pengeluaran per kapita untuk memenuhi kebutuhan 2100 kalori per hari, masih bicara kebutuhan fisiologis, tak ubahnya dengan statistik zaman kolonial.
Ukuran itu hanya menciptakan “gelembung citra”, bukan menggambarkan realitas. Ketika BPS mengkaim angka kemiskinan terendah dalam sejarah, negeri ini justru belum lepas dari bahaya gizi buruk dan kelaparan.
Pantauan Status Gizi (PSG) 2017 yang dilakukan Kementerian Kesehatan menemukan, bayi usia di bawah lima tahun (Balita) yang mengalami masalah gizi pada 2017 mencapai 17,8 persen dan stunting sebesar 29,6 persen.
Ironisnya lagi, berselang beberapa saat setelah BPS mengumunkan angka kemiskinan yang terendah dalam sejarah itu, ada 4 warga suku Mause Ane di Maluku Tengah, Maluku, yang meninggal karena kelaparan.
Kita butuh ukuran kemiskinan yang multi-dimensi. Tidak hanya mengukur kebutuhan fisiologis, tetapi semua kebutuhan dasar manusia untuk maju dan berkembang.
Kita butuh ukuran kemiskinan yang sejalan dengan politik kemakmuran. Karena memang Indonesia diperjuangkan dan merdeka karena cita-cita besar: masyarakat adil dan makmur.
(Red/Ksh)
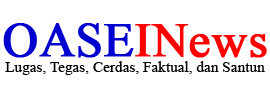


Tinggalkan Balasan